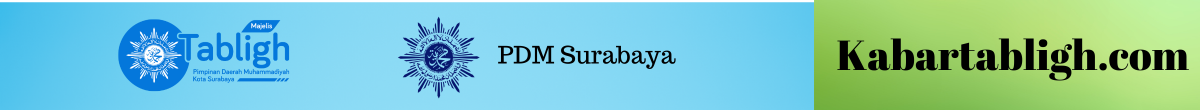Konsep Ulil Amri dan Persoalan Ketaatan

Konsep Ulil Amri dan Persoalan Ketaatan
Muh. Waluyo, Lc., M.A.[1]
- Pendahuluan
Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, dipimpin oleh seorang muslim tetapi parlemen tidak dikuasai kekuatan politik Islam. Perlu kiranya adanya kesiapan kita untuk memulai membuka wacana yang lebih luas tentang pemaknaan ulil amri sehingga tidak terjebak dalam pengertian yang sempit yang menyebabkan kita hidup dalam alam cemerlang tetapi dalam kezumudan.
Al Qur’anul Karim menyebut ulil amri dalam surat An-Nisa ayat 59 dan 83: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rosul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. 4:59)
“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya kepada Rosul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rosul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja (diantaramu).” (Q.S. 4:83)
Dari ayat tadi, secara derajat “ulil amri” merupakan derajat ketiga dalam penyebutan yaitu setelah Allah SWT dan Rosululloh Saw. Dengan demikian bukan sesuatu yang berlebihan apabila ulil amri diberi derajat yang tinggi karena memang telah disebut dalam derajat yang demikian. Dalam kenyataan kemasyarakatan jarang (atau tidak pernah digunakan) sebagai sebutan resmi bagi sesuatu atau seseorang. Oleh karena itu, masih menjadi masalah yang membutuhkan pendalaman tentang arti kata ulil amri itu sendiri. Selain itu, menjadi pertanyaan lanjutan apakah arti kata ulil amri itu sendiri.
Selain itu, menjadi pertanyaan lanjutan apakah ulil amri itu suatu institusi atau hanya merupakan sebutan kepada seseorang. Penentuan atas dan untuk apa sebutan ini diadakan akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang tindak lanjut perlakuan objektif dan subjektif kepada pihak lainnya. Hal ini berhubungan dengan kenyataan bahwa dalam keseharian dibidang politik lebih dikenal istilah kholifah, amir, imam, dan sultan.
Namun demikian, dalam pencaturan politik di Indonesia, kata ini (sebagai terjemahan dari Surat An Nisa 59) pernah populer selama tiga dekade yaitu pada era 70 – 90 an ketika negara dan bangsa dikuasai oleh politik kekaryaan. Kata ini menjadi jargon politik pemaksaan penundukan masyarakat kepada penguasa yang cukup dominan dan memberi pengaruh yang signifikan bagi legitimasi penguasa untuk menguasai panggung perpolitikan nasional. Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini hanya akan memfokuskan pada masalah pengertian ulil amri dan batas ketaatan kepada ulil amri.
Khusus tentang persoalan ulil amri, yang jadi persoalan bukanlah tentang keharusan patuh pada ulil amri, karena perintah patuh pada ulil amri sudah dinashkan secara jelas dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’ 4: 59)
Tetapi yang jadi persoalan adalah siapakah yang berhak disebut ulil amri dalam ayat tersebut. Satu pihak menyatakan bahwa ulil amri itu adalah pemerintah. Untuk urusan penetapan awal Ramadhan dan terutama awal Syawal, ulil amrinya adalah Menteri Agama. Dengan demikian, apabila Pemerintah sudah menetapkan awal bulan Ramadhan dan Syawal, maka semua umat Islam harus mematuhinya. Dalam hubungannya dengan Muhammadiyah, jika Muhammadiyah mengumumkan berbeda dengan Pemerintah, berarti Muhammadiyah tidak taat dengan ulil amri, berarti juga tidak melaksanakan perintah Allah dalam ayat di atas. Sementara itu, pihak lain, terutama Muhammadiyah, tidak menolak kewajiban patuh dalam ayat tersebut? Tapi yang dipertanyakan adalah apakah menteri agama itu sah disebut sebagai ulil amri? Untuk urusan keagamaan, apalagi ibadah mahdhah, harusnya diputuskan oleh lembaga yang punya kompetensi dan otoritas untuk itu? Misalnya di Mesir yang memutuskan satu Syawal adalah Grand Mufti, sementara Mentri Agama/Wakaf hanya menyaksikan, di Saudi Arabia yang memutuskan adalah Mahkamah Agung, di Malaysia yang memutuskan adalah Mufti Negara.
Dan sebagian besar negara-negara Islam yang memutuskan adalah mufti. Mufti atau grand mufti ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan kriteria keulamaan dan keahlian dalam agama. Sementara di Indonesia menteri agama adalah jabatan politik, ditunjuk oleh presiden berdasarkan pertimbangan politik bukan pertimbangan keulamaan. Indonesia tidak mempunya mufti atau grand mufti. Oleh sebab itu selama ini fatwa-fatwa keagamaan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa yang ada pada ormas-ormas Islam seperti Majlis Tarjih dan Tajdid (Muhammadiyah), Lajnah Bahsil Matsail (Nadhlatul Ulama) atau komisi fatwa (Majelis Ulama Indonesia).
Makalah ini mencoba membahas tentang masalah Ulil Amri ini. Apa pengertian ulil amri dan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ulil amri tersebut.
- Pengertian Ulil Amri
Ulil amri sebuah kata yang disebutkan dalam Al-Qur’an tetapi jarang digunakan dalam keseharian sehingga penulis hanya menemukan sedikit pustaka yang membahas tentang ulil amri yang berbahasa Indonesia. Padanan kata ulil amri dalam Al-Qur’an antara lain, Ula al albab (pemikir), ula al-quwwah (yang memiliki kekuatan/kekuasaan), ulu al-aidi (orang yang memiliki kekuatan, yang dilambangkan dengan tangan yang kuat), ulu al-ilm (para pakar), ulu al-fadl (yang memiliki kedudukan istimewa) ulu al-ba’s (orang-orang yang peduli), ulu azmi, dan ulu al-absar (orang yang memiliki proyeksi masa depan)[2].
Dalam catatan kaki terjemahan Al-Qur’an Depag, kata ulil amri dalam surat An Nisa 59 adalah tokoh-tokoh sahabat dan para cendekiawan[3]. Catatan kaki tersebut tidak menjelaskan kedudukan dari mereka yang disebut ulil amri tetapi lebih menunjukkan kepala golongan. Ulil amri secara etimologi berarti pemimpin dalam suatu negara. Istilah ini terdapat dalam pembahasan tafsir dan fiqh siyasah (politik)[4]. Para ulama tafsir dan fiqh siyasi mengemukakan empat definisi ulil amri yaitu :
- Raja dan kepala pemerintahan yang patuh dan taat kepada Allah SWT dan Rasululloh Saw;
- Raja dan ulama
- Amir di zaman Rosululloh Saw. Setelah Rosululloh wafat, jabatan itu berpindah kepada haki (hakim), komandan militer, dan mereka yang meminta anggota masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran; dan,
- Para mujtahid atau yang dikenal dengan sebutan ahl al-halli wa al-‘aqad[5]
Namun demikian, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho mengartikan ulil amri sebagai pemegang otoritas di sebuah negara yang terdiri dari penguasa, para hakim, ulama, komandan militer, dan pemuka masyarakat yang menjadi rujukan umat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Risyad Ridho lebih meluaskan arti ulil amri ini dengan memasukan mereka yang memiliki otoritas di bidang kesehatan, perburuhan, perniagaan, pemimpin media massa, dan pengarang[6].
Secara sederhana, Fachrudin mengartikan ulil amri sebagai pemimpin yang bertugas atau ditugaskan mengurus sesuatu urusan misalnya pemerintahan, ketentraman, perjuangan dan pembangunan dalam berbagai lapangan, umumnya yang menjadi kepentingan bersama[7]. Sementara itu, Abdul Wahab Khallaf memberikan arti ulil amri sehubungan dengan sumber hukum menyatakan bahwa lafad al amr berarti perkara atau keadaan, bersifat umum karena dapat menyangkut masalah agama dan keduniaan. Dari pengertian tersebut, ia membagi penyebutan atas kelompok tersebut yaitu untuk ulil amri dalam urusan dunia adalah raja, pemimpin, dan penguasa; untuk urusan agama adalah para mujtahid dan ahli fatwa[8]. Sementara itu, Ibnu Abas memaknai ulil amri pada ayat (Q.S. 4:59) tersebut sebagai ulama; ulama tafsir lain menyebut sebagai umara dan penguasa. Namun demikian menurut Abdul Wahab, kata tersebut mencakup semuanya termasuk kewajiban taat kepada kelompok penafsir tentang masalah yang harus ditaati[9].
Menurut sebagian ulama, karena kata al-amr yang berbentuk ma’rifah atau difinite, maka wewenang pemilik kekuasaan terbatas hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan semata, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni. Untuk persoalan aqidah dan keagamaan murni harus dikembalikan kepada nash-nash agama (Al-Qur’an dan As-Sunnah). Hal ini selaras dengan pemikiran Muhammad Abduh. [10]
Dalam hal ini tampak bahwa perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi dalam pemahaman terhadap nash, bukan dalam mematuhi nash. Dalam masalah hadits tentang tata cara untuk mengetahui awal Ramadhan dan awal Syawal, persoalannya bukan pada masalah patuh atau tidak patuh pada petunjuk Rasul tersebut, tetapi tentang bagaimana memahami hadits tersebut.
Menurut pandangan Muhammadiyah, hadits itu ada ‘illatnya, yaitu karena umat pada masa itu belum mempunyai cara lain untuk mengetahui awal bulan kecuali dengan melihat hilal. Kalau gagal melihat hilal karena mendung, maka bulan yang sedang berjalan itu digenapkan 30 hari. Sekarang, ilmu astronomi sudah demikian maju, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui awal bulan. Oleh sebab itu Muhammadiyah yakin tidak melanggar sunnah tatkala menggunakan hisab hakiki untuk menentukan awal bulan. Sebagian memahami, bahwa yang bersifat ta’abbudi (tidak boleh dirubah sedikitpun) adalah puasa Ramadhan dimulai tanggal 1 Ramadhan dan shalat ‘Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Sedangkan bagaimana cara menentukan awal Ramadhan dan awal Syawal itu adalah sesuatu yang bersifat ta’aqquli (rasional, dapat berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan lebih bersifat teknis.
Dari uraian di atas, ternyata bahwa ulil amri tidak semata-mata mereka yang mempunyai otoritas dibidang keilmuan, kemasyarakatan, dan keduniaan lainnya. Dengan demikian, ulil amri hanya merupakan sebutan umum untuk mereka yang mempunyai kewenangan tertentu sesuai dengan bidangnya.
- Syarat Ulil Amri
Muhammad Abduh dengan mendasarkan kepada surat An Nisa 59 menyatakan, kepada mereka inilah harus taat dan patuh selama mereka menaati Allah SWT dan Raosululloh Saw[11]. Para mufasir menyatakan bahwa dalam ayat ini untuk ulil amri tidak didahului dengan kata ali’u memberikan makna bahwa ketaatan hanya diharuskan selama ulil amri taat kepada Allah SWT dan Rosululloh Saw. Pendapat ini bersesuaian dengan hadis “Seorang muslim wajib mendengar dan taat (kepada para pemimpin) terhadap yang ia senangi atau ia benci, kecuali jika disuruh berbuat durhaka, ia tidak boleh mendengar dan taat (HR Muslim dan Ibnu Umar)[12].
Penggunaan kata ulil amri digunakan dalam bidang lain dan bagaimana batas keharusan taat kepada seorang ulil amri dilukiskan dalam suatu hadis yang menceritakan tentang panglima perang. Rosululloh Saw mengirim satu pasukan dan mengangkat untuk komandannya seorang laki-laki dari kaum Anshar. Setelah berangkat, komandan kurang senang terhadap anak buahnya, lalu ia berkata : “Bukankah Rosululloh Saw menyuruh kamu supaya mematuhi perintahku?” Mereka semua menjawab “ya”. Perintahnya : “Kamu kumpulkan kayu api kemudian kayu itu dibakar sampai menyala, lalu saya perintahkan kamu semua masuk ke dalam api itu”. Seorang pemuda diantara mereka menjawab “kami semua datang kepada Rosululloh Saw supaya terhindar dari api. Sebab itu, janganlah kamu memasuki api sebelum kita bertemu dengan Rosululloh Saw. Kalau beliau menyuruh kita masuk api, tentu kita akan masuk kedalamnya”. Mereka segera kembali menemui Rosululloh Saw, dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Rosululloh Saw bersabda, “Kalau kamu masuk ke dalam api itu, niscaya kamu tidak akan keluar dari situ untuk selamanya. Hendaknya kamu patuhi perintah dalam hal-hal yang baik”. (HR Bukhori, Muslim, dan Achmad)[13]
Dalam konteks politik ulil amri pertama kali diperkenalkan oleh Umar bin Khotab ra dengan membentuk suatu lembaga yang bertugas membantu amirul mukminin yang disebut ahl al hall wa al-a’qad. Badan ini melakukan tugas melalui musyawarah untuk mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan kepentingan umum yang bersifat keduniaan dengan tugas pokoknya amar makruf nahi munkar. Dengan demikian, konsep ulil amri berhubungan erat dengan konsep musyawarah (QS 2:233, 3:159; 42:38), konsep amanah (QS. 4:58), dan konsep amar makruf nahi munkar (QS. 3:104)[14].
Ulil amri bertugas melayani keperluan orang banyak, mempunyai tanggung jawab yang berat, jujur, niat baik, memudahkan dan mempercepat, memberikan bantuan, urusan karena ia sebagai seorang petugas[15].
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa ulil amri mempunyai makna yang luas dalam konteks kehidupan keumatan baik segi keduniaan maupun agama. Dengan keluasan ini maka ulil amri tidak harus selalu berada pada bidang politik atau kekuasaan tetapi juga dapat berada pada setiap unit kegiatan kemasyarakatan dan setiap tingkatan (strata) baik yang berada pada tataran konsep maupun teknis operasional. Dengan demikian ulil amri akan dekat dengan kewenangan dan kekuasaan (authority dan power). Jadi ulil amri dapat berjalan karena berdasar pada kewenangan, kekuasaan, atau kekuasaan dan kewenangan; baik didapat secara original ataupun delegasi.
Secara general ulil amri dapat digolongkan pada dua golongan yaitu golongan yang berada pada wilayah kekuasaan/politik negara dan golongan yang berada pada keilmuan. Pada golongan yang pertama dapat berupa kholifah, amir, sultan, panglima militer, pejabat negara, dan profesi lainnya, sedangkan dalam golongan kedua tercakup ulama, mujtahid, dan ahli pikir lainnya. Oleh karena itu, ulil amri dapat dikatakan sebagai konsep, institusi bukan menunjuk pada subjek person sehingga untuk menentukan siapa yang dapat disebut dan siapa yang dapat menjadi ulil amri memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Hal ini sesuai dengan kandungan hadis dalam sahih Bukhori : Apabila amanat itu dilenyapkan, maka tunggulah datangnya kiamat. Dikatakan kepada Beliau Wahai Rosululloh, bagaimana melenyapkan amanat itu? Rosululloh Saw bersabda, Apabila perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat.
Syarat seorang ulil amri dalam bidang umaro ini secara mendasar harus Ashlah (paling layak dan sesuai)[16]. Hal ini berhubungan dengan quwwah (otoritas), dan memegang amanah (jujur dan dapat dipercaya), mengurus masyarakat, dan hubungan perwakilan antara yang pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya; jangan memberikan kepada yang meminta[17], karena kesukuan, kekerabatan, atau karena hal lain yang menyimpang dari agama. Apabila kriteria di atas tidak ditemukan maka pilihan harus dijatuhkan pada yang terbaik dari yang ada. Pada golongan ini, secara kualitas sudah baik tetapi masih terdapat kekurangan yang nyata. Namun demikian apabila dilakukan secara optimal maka hak-hak wilayat (jabatan) sudah terpenuhi[18].
Apabila yang mempunyai quwwah dan sekaligus amanat tidak ada, maka prioritas ditujukan pada kebutuhan dan kapasitas calon yang dipilih. Dalam jabatan panglima perang misalnya, apabila pilihan harus ditentukan dari beberapa orang yang ada dengan banyak kesamaan maka pilihan harus dijatuhkan pada orang yang mempunyai sifat pemberani dan kuat secara pisik[19]. Rosululloh Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah akan memperkuat posisi agama ini (Islam) dengan orang yang fajir (suka berbuat dosa) (HR Bukhori). Sehubungan dengan itu, Kholid bin Walid selalu diangkat menjadi panglima walaupun dalam keseharian ia sering melakukan perbuatan yang tidak disukai Rosul Saw. Suatu ketika Rosululloh Saw, mengadahkan tangannya ke langit seraya berdo’a Ya Allah akan berlepas diri kepada Mu dari apa yang diperbuat Kholid.
Pemilihan berdasar ini pernah dicontohkan ketika Rosululloh memilih Kholid bin Walid dan tidak memilih Abu Dzar[20]. Padahal tidak ada orang yang paling jujur perkataannya melebihi Abu Dzar. Jadi syarat bagi ulil amri ini selain sifat dasar akan tergantung juga pada syarat-syarat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nyata akan jabatan yang disandangnya. Keuangan sangat membutuhkan kejujuran, dan untuk hakim dibutuhkan orang yang mampu bertindak adil dan kuat persaksiannya (komitmen terhadap agama)[21].
- Ulil Amri Bidang Pemerintahan
Secara umum dalam wacana Islam dikenal beberapa sebutan untuk kepala pemerintahan yaitu kholifah, imam, sultan dan amir. Kholifa, Amir, dan Sultan lebih dikenal dalam sistem politik Islam sunny, sedangkan imam lebih dikenal dalam masyarakat yang bersistem politik syi’i. Dalam masyarakat dikenal pula nama lain yaitu sunan sebagaimana disandang para wali songo yang diakui sebagai pemula penyebar Islam dan pendiri kerajaan Islam di tanah Jawa, sedangkan Imam pernah disandang leh Kepala Negara Islam Indonesia S.M. Kartosuwirjio
- Khalifah[22]
Pemerintah dengan sebutan kholifa ini terbagi dalam dua periode yaitu kholifaturrasyidin (kholifa yang lurus – kholifah empat) dan kholifah yang setelahnya sampai dengan Kholifa Turki Utsmani. Kholifa yang empat dipilih dari para sahabat dekat Rosululloh Saw sejak awal sudah memenuhi kriteria banyak aspek atau mumpuni. Ini lebih didasarkan pada fakta. Namun demikian, Kholifa empat ini semuanya dari golongan muhajirin. Selain itu, kalau dilihat dari hubungan dengan Rosululloh Saw semuanya mempunyai hubungan semenda.
Cara pengisian kholifa empat ini adalah dipilih walaupun dengan cara berbeda-beda dari satu khlaifa kepada kholifah lainnya. Abu Bakar dipilih oleh musyawarah Elit Sahabat dari Anshar dan Muhajirin; Umar ra dicalonkan oleh Abu Bakar setelah Abu Bakar setelah Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat lainnya; Utsman dipilih oleh formatur yang dibentuk oleh Umar dengan ketua Abdurrahman bin Auf; sedangkan Ali ra dipilih secara spontan oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan kepala pemerintahan[23]. Akan tetapi inti yang terkandung dari cara pemilihan kholifa empat ini adalah adanya musyawarah dan tidak berdasar keturunan. Kholifah berfungsi sebagai amirul mukminin, bapaknya orang-orang mukmin. Oleh karena itu ia berperan sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, imam, dan hakim sekaligus juga mujtahid dibidang hukum. Untuk menjalankan fungsi dan peran tersebut, para kholifah ini mempunyai suatu badan semi legislatif untuk membantu memecahkan masalah-masalah baik kemasyarakatan maupun keagamaan.
Masa jabatan kholifah tidak ada batas waktunya karena semua kholifa menjabat sampai maut menjemputnya kecuali ketika kholifa Ali bin Abi Thalib yang direbut kekuasaannya oleh Muawiyah seorang gubernur di daerah Damaskus dan masih dari kalangan Quraisy melalui tahkim (arbitase) yang direkayasa oleh Amr bin Ash yang nantinya diangkat salah seorang Gubernur di masa pemerintahan Muawiyah. Daerah kekuasaan kholifa meliputi seluruh negara Madina setelah perluasan yaitu Negara Madina ditambah daerah baru hasil ekspedisi kaum Muslimin. Namun demikian, dalam beberapa hal walaupun secara de yure termasuk daerah kekuasaan kholifa tetapi de facto ada juga daerah yang dikuasai oleh amir atau sultan yang membangkang terutama di masa kekholifahan Ali Bin Abi Thalib.
Pada periode kholifa kedua yaitu sejak Muawiyah menjadi kholifa, diteruskan dengan Dinasti Abasiah, sampai pada Turki Utsmani, pengisian kholifa tidak lagi melalui musyawarah atau pemilihan tetapi melalui keturunan. Dalam bidang-bidang lainnya masih sama tetapi sesuai perkembangan jaman, badan-badan baru yang dipimpin oleh ulil amri dibidangnya mulai dikembangkan. Kholifa setelah kholifa keempat merupakan raja. Dengan demikian tidak ada keterlibatan pihak lain atau masyarakat atau warga negara dalam menentukan kholifa. Fungsi dan kewenangannya, pada mulanya baik Muawiyah maupun Abasiah sama seperti kholifaturrasyidin yaitu menjadi ulil amri dibidang kenegaraan dan keagamaan. Akan tetapi dalam perkembangannya, kholifa mulai kekurangan otoritas dibidang keagamaan sehingga fungsi ini dijalankan oleh pihak lain yang mempunyai otoritas keagamaan.
Dengan demikian ada dua hal yang mengalami perubahan mendasar yaitu cara pengisian jabatan dan berkurangnya fungsi kholifa sebagai imam. Namun demikian dalam perjalanan sejarah ulil amri bidang politik dan ulil amri bidang keagamaan terjadi saling ketergantungan. Hal ini dibuktikan bahwa suatu mazhab dapat hidup tumbuh subur dan berkembang kalau ia diakui secara resmi oleh ulil amri bidang publik (kholifa); sebaliknya ulil amri bidang publik minta otoritas ulil amri bidang agama untuk memperlancar programnya.
Sebagai catatan, pada masa kekholifahan ini tidak ada satupun yang membuat konstitusi. Semuanya tetap berdasar Al-Qur’an dan As Sunnah serta ijtihad. Konstitusi mulai dikembangkan pada saat masa akhir kekuasaan Turki Utsmani abad ke 20. Selain itu, dalam masa kholifa periode kedua pernah terjadi muslimin dipimpin oleh dua kholifa yaitu kholifa Bagdad dan kholifah Andalusia di Spanyol.
- Sultan
Selain kholifa ada juga ulil amri yang disebut sultan. Pada dasarnya sultan dengan kholifa secara perjalanan sejarah tidak jauh berbeda karena kedua-duanya merupakan penguasa negara, pemimpin masyarakat tetapi diisi melalui keturunan (dinasti), dan wilayah kekuasaannya lebih kecil terkadang hanya satu wilayah propinsi. Sultan-sultan ini merupakan pecahan negara Islam dalam wilayah-wilayah kecil; ketika otoritas kholifa masih kuat, para sultan masih tetap mengakui bahwa pemimpin adalah kholifa tetapi ia mempunyai otoritas sepenuhnya atas daerah yang dikuasainya.
Di Indonesia misalnya, sebelum direbut oleh penjajah (Eropa) terdiri dari banyak kesultanan. Kesultanan pertama yang tumbuh di Jawa dipimpin oleh Wali Songo. Para Wali Songo ini mempunyai wilayah kekuasaan masing-masing, tetapi satu sama lain selalu berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi adalah Sultan Demak. Sisa kesultanan Islam di Indonesia yang masih hidup antara lain adalah Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat sebagai penerus dari Kerajaan Mataram Islam dengan Sultan sebagai simbol kebudayaan. Para sultan ini biasanya menggunakan gelar kholifa juga. Sultan Hamengku Buwono IX menggunakan gelar Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Abdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah IX[24].
Sementara itu kesultanan yang masih hidup di sekitar kita adalah di Malaysia dan Brunei, di Malaysia, sultan tidak mempunyai kekuasaan kenegaraan hanya sebagai lambang karena kekuasaan yang sesungguhnya ada pada pemerintah federal yang dipimpin oleh perdana menteri. Sedangkan di Brunei, sultan mempunyai kekuasaan penuh atas negara dan warga negara Brunei.
- Amir
Selain kholifa dan sultan, masih ada gelaran lain untuk ulil amri yang biasa digunakan yaitu amir/emir. Kata ini lebih menunjukkan pada penguasa karena kholifa empat pun selalu disebut dengan amirul mukminin, arti khusus yang diberikan kepada amir dalam wacana politik sesungguhnya penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Jadi ia merupakan aparat pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah[25]. Telah dikemukakan bahwa ulil amri tidak menunjuk pada suatu jabatan tertentu. Oleh karena itu, disamping kepala negara yang disebut ulil amri mencakup mereka yang mempunyai otoritas mengurus kepentingan negara dan masyarakat. Cara pengisiannya ditentukan oleh pejabat yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan. Kewenangannya terbatas pada bidang yang ia tempati karena ia pada dasarnya hanya mewakili. Dengan demikian otoritasnya tidak orisinal tetapi merupakan otoritas delegasi.
- Ulil Amri di Bidang Keagamaan/Keilmuan
Dalam bidang keagamaan, mereka yang mempunyai otoritas adalah ulama yang ajarannya banyak diikuti. Banyak cabang yang dilahirkan dari para ulama ini karena dapat berupa fiqh, hadits, torekat, tasawuf, dsb. Untuk fiqh, misalnya dikenal empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali[26]. Sementara untuk hadits yang paling dikenal adalah Bukhori dan Muslim; dan untuk tasawuf Syatariyyah dan Naksyabandiyyah.
- Fiqh
Dalam bidang fiqh secara umum ajarannya mandiri. Kemunculan tokohnya diawali dengan penyebarluasan ajaran dan dibesarkan oleh murid atau pengikutnya. Sifat ketaatan kepada ulil amri bidang fiqh ini pernah sangat kuat, sehingga tidak akan bercampur satu ajaran dengan ajaran lainnya. Sifat muqollid sangat dominan. Padahal para pendiri mazhab tidak pernah menyatakan bahwa ajarannya yang paling benar.
Hal ini bisa terjadi karena kerangka atau pola pikir selalu dipegang teguh. Sampai saat ini pun, keadaan tersebut masih nampak sisa-sisanya karena masih sering terjadi polarisasi yang tajam antar elit agama yang bertolak dari permazhaban ini. Sesungguhnya ketaatan sesorang terhadap ulil amri dalam bidang keagamaan ini tidak ada paksaan. Akan tetapi karena yang dibentuk oleh pemikir fiqh ini adalah pola pikir, maka ketaatan terjadi dengan sendirinya walaupun tanpa ada yang memerintahkan.
- Tarekat
Berbeda dengan itu, ulil amri dalam bidang tarekat disebut dengan imam, guru, atau syeikh. Tarekat dipimpin oleh seorang yang dianggap telah suci dari segala kemungkaran dan kenistaan dunia, raga dan jiwa. Dengan demikian apa yang dilakukan atau dicontohkan guru adalah benar adanya. Oleh karena itu, seorang murid atau pengikut harus taat kepada guru dan syeikhnya. Abubakar Aceh mengetengahkan tidak kurang dari 24 syarat-syarat seorang dapat diangkat sebagai syeikh; dan mengemukakan 27 akhlak seorang murid terhadap guru. Dari kedua puluh tujuh akhlak murid kepada guru itu antara lain, menyerahkan diri dan tunduk sepenuh-penuhnya kepada guru, tidak boleh menentang atau menolak apa yang dikerjakan gurunya, berkat yang diperoleh seorang murid disebabkan berkat guru, dan selalu mengingat syeikh baik ketika hadir maupun tidak hadir[27]. Dengan demikian bagi seorang murid dalam suatu aliran tasawuf atau thotekat sangat diwajibkan; tidak boleh tidak. Seorang murid yang tidak taat akan dikeluarkan atau tidak dianggap lagi sebagai murid atau pengikut.
- Ilmu Lainnya
Apabila kita menyetujui pengertian ulil amri sebagaimana diuraikan di atas, maka ulil amri mencakup pula bidang keilmuan lain. Bidang keilmuan yang pernah berkembang pada masa kejayaan Islam mencakup berbagai bidang, dan sebagian besar pengembangnya adalah para ahli tasawuf. Seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi. Karya mereka tidak terbatas pada satu bidang ilmu tetapi mencakup berbagai aspek keilmuan. Al-Kindi misalnya, menulis risalah dari mulai filsafat, logika, ilmu hitung, dimensi sampai dengan logam dan kimia[28]. Ar Rozi menulis tentang kedokteran, fisika, ateisme, teologi, dll[29]. Ibnu Sina selain kedokteran juga teologi, Al-Farabi menulis tentang logika, teologi, matematika, fisika, dsb[30].
Patut diingat pula bahwa mereka pun mengembangkan filsafat ketuhanan dan kenabian yang terkadang cukup menohok pemikiran mapan kita. Ibnu Sina misalnya, mengemukakan “Yang pokok itu Allah sebagai pangkal gerak, tetapi ia tidak sampai mengetahui yang kecil-kecil karena tidak perlu bagi Allah, Alam dunia ini bersifat azali, yang hanya perubahan bukan kehancuran”[31].
Ketaatan terhadap ulil amri di bidang keilmuan ini sifatnya terbuka karena ilmu terbuka; jadi, sangat tergantung kepada masing-masing. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa sesungguhnya dalam bidang keilmuan yang mereka ubah bukan pisik tetapi pikiran sehingga dengan perubahan pikiran ini kita akan didorong untuk mentaati ajarannya, walupun tidak ada paksaan.
- Perkembangan Ulil Amri di Bidang Politik
Di negara-negara yang menjalankan syari’at Islam atau mayoritas berpenduduk Islam sejak berakhirnya Perang Dunia I hanya sedikit yang masih menggunakan istilah-istilah yang berasal dari Islam karena lebih banyak menggunakan istilah yang berasal dari konsep Rumawi atau Barat yang bernotabene berdasar pada filsafat Kristiani dan Yahudi yaitu King/Raja atau Presiden. Negara-negara di Timur Tengah sebagian besar menggunakan raja atau presiden, hanya sedikit yang menggunakan Amir/Emir atau sultan seperti di Oman, Kuwait, Uni Emirat Arab.
Oleh karena itu penyebutan kepada ulil amri di bidang politik lebih menunjuk pada institusi atau wadah. Dengan demikian penyebutan kepala negara tidak memberikan salah satu ciri sebagai negara Islam atau bukan. Sementara itu, dari segi otoritas ternyata bahwa kholifaturrasyidin merupakan ulil amri yang paling luas otoritasnya karena ia memiliki otoritas dalam segala aspek kehidupan baik politik, sosial, ekonomi, agama dan lainnya. Kholifa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan imam. Umar bin Khotab ra misalnya, selain terkenal sebagai ahli bidang ekspedisi militer juga paling terkenal dengan ijtihadnya,. Utsman bin Affan dikenal sebagai peletak dasar dalam tata pemerintahan. Pada saat itu, kholifah sebagai kepala pemeerintahan masih sering merangkap menjualankan fungsi pengadilan sehingga iapun masih menyelesaikan sengketa atau mengadili pelaku kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.
Setelah berakhirnya sahabat yang empat, kepemimpinan Islam beralih dari sistem pemilihan kepada sistem dinasti dimulai oleh dinasti Muawiyah dan Abasiah. Pengisian kholifa bergeser dari sistem dipilih menjadi berdasar keturunan. Kewenangannya pun menjadi luas di bidang pemerintahan tetapi menyempit di bidang keagamaan. Mulai masa itu, kholifa bukan lagi ahli agama tetapi semata-mata karena keturunan kholifa sebelumnya. Model ini terus digunakan oleh penguasa-penguasa di negara muslim yang muncul belakangan; bahkan pernah terjadi kholifa masih berusia di bawah umur belum akil balig. Dengan demikian kepala negara/pemerintahan tidak secara sekaligus menjadi imam.
Kekholifahan berakhir bersamaan dengan runtuhnya Turki Utsmani tahun 1942 yang kemudian disuksesi oleh Turki Modern yang sekuler oleh Kamal Attaturk. Di Indonesia pada waktu mulai munculnya kerajaan-kerajaan Islam, para sultan sekaligus sebagai ulama. Tetapi selanjutnya tidak jauh berbeda dengan keadaan di negara Islam pasca kholifa empat. Dengan perkembangan demikian, dibentuk atau ditunjuk suatu badan yang mengurusi keagamaan yang biasanya merangkap sebagai imam mesjid. Dari kondisi ini, di Indonesia muncul suatu istilah tempat ulama atau ahli agama yang secara resmi digunakan oleh negara yaitu kauman.
Dari uraian di atas, pemilihan ulil amri pada mulanya bertolak pada integritas keimanan, keilmuan agama, dan akhlak, bukan pada faktor lain di luar itu. Tetapi karena sistem yang berubah maka pemilihan ulil amri lebih mengedepankan nasab; dan pada perkembangan selanjutnya lebih mengutamakan kehebatan dari pada ketiga unsur tadi.
- Ketaatan Kepada Ulil Amri
- Umum
Pada zaman Kholifa empat karena kholifa sekaligus imam maka sikap masyarakat sangat taat. Hal ini didasarkan pada legitimasi bahwa kholifah adalah segala-galanya sebagai pengganti Rosulullah Saw; dan kepada kholifa terpilih selalu dilakukan baiat yang biasanya dimulai dengan baiat dari sekelompok ulil amri (elit) kemudian baiat umum oleh seluruh masyarakat. Sedangkan dalam perkembangan selanjutnya sepeninggal kholifa empat, ketaatan masyarakat tidak lagi diwujudkan secara bulat. Sering terjadi seorang ulama secara terang-terangan menentang kholifa; dan akibatnya banyak ulama dipenjarakan oleh kholifa sebagai ulil amri. Karena ketaatan kepada ulil amri bergantung pada otoritas, legitimasi, dan sebab timbulnya ulil amri yang bersangkutan, maka akan tergantung pula pada jenis ulil amri. Dengan kata lain, kewenangan ulil amri sesungguhnya akan tergantung pada jenisnya. Ulil amri di bidang pemerintahan ia mempunyai kewenangan membuat dan melaksanakan aturan sesuai dengan tingkatan ia berada, dan sesuai pula dengan cara pengisian jabatan tersebut. Kalau ia diangkat oleh pejabat diatasnya maka ia hanya mempunyai kewenangan yang sifatnya delegasi sehingga ia tidak dapat membuat peraturan atau perintah yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh orang yang mengangkatnya. Dengan demikian teori hirarki peraturan berlaku pula bagi ulil amri.
Dengan tetap berdasar pada sumber utama Al Islam, produk hukum pada bidang pemerintahan kalau berdasar syariat harus selalu mengajak berbuat kebaikan dan mengajak untuk mencegah kemunkaran; Dari sini elaborasi dalam aturan apapun tidak boleh menyimpang dari prinsip ini. Apabila peraturan telah dibuat dan aturan telah diberlakukan, penerapan aturan tersebut harus tetap melihat kepada maslahat tanpa menyimpangi aturan hukum. Ada dua peristiwa yang pantas dijadikan pelajaran.
Pertama, ketika zaman Rosululloh Saw akan menghukum rajam bagi wanita yang berzina dan ketika diketahui sedang hamil, maka Rosul Saw menunda eksekusi sampai melahirkan. Setelah melahirkan eksekusi ditunda kembali sampai habis masa menyusui; hukuman baru dilaksanakan setelah habis masa menyusui[32].
Kedua, dilakukan oleh Umar bin Khotab r.a. yaitu ketika ada warga yang mencuri. Secara hukum apapun alasannya orang mencuri harus dihukum, karena tidak dikenal alasan pembebas. Tetapi setelah diketahui bahwa orang tersebut melakukan pencurian disebabkan keadaan lapar, Amirul Mukminin tidak memberikan hukuman malahan menyalahkan masyarakat yang menimbulkan kepadaan lapar tersebut[33]. Dengan demikian pemegang otoritas pelaksana hukum bukan suatu institusi yang harus melepaskan diri dari rasa keadilan dan maslahat karena tetap harus mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan.
Dalam bidang pemerintahan keharusan untuk taat kepada ulil amri lebih mudah mengukurnya baik secara objektif maupun subjektif karena banyak unsur dan parameter yang dapat digunakan selain prinsip utama yang telah disebutkan diatas. Ketaatan kepada ulil amri bidang publik ini ada batasnya, bahkan seseorang yang sedang berkedudukan sebagai ulil amri dan ia telah menyimpang dari syariat Islam, ia harus diganti. Pernyataan harus menandakan bahwa penggantian dapat dilakukan secara baik-baik atau secara paksaan, yang dalam bahasa kesehariaan dikita kenal dengan sebutan kudeta.
Sebenarnya yang perlu mendapat perhatian adalah ketaatan kepada ulil amri dari golongan yang berada pada bidang agama, fiqh, dan syar’i karena golongan ini tidak meminta untuk taat tetapi mengubah pikiran untuk taat. Pada perkembangan hukum Islam pernah terjadi perkembangan yang sangat menonjol dari pemikiran fuqoha. Tidak ada satu imam fiqh pun yang mengharuskan penganutnya untuk mentaati pendapat atau fatwanya[34]. Gagasan keilmuan ia lemparkan kepada murid dan ke tengah masyarakat sebagai wacana yang terus berkembang. Hasilnya mengenal fanatisme yang kadang berlebihan terhadap suatu mazhab.
Dari keadaan ini.lahirlah istilah zaman kejumudan yaitu seolah-olah pintu ijtihad telah tertutup, padahal tidak ada yang menutup dan tidak ada yang melarang berijtihad. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan yang mendasar apakah benar ijtihad ditutup? Atau ajaran fuqoha dalam menafsirkan Al-Qur’an dan Hadits dirasa cukup sehingga belum ada kebutuhan untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Adalah suatu keniscayaan manusia dalam hidupnya bahwa ia akan selalu memerlukan sesuatu yang dapat memuaskan jiwanya termasuk dalam urusan fiqh.
Selain itu, perlu pula menjadi perhatian tentang arti kezumudan itu sendiri. Kezumudan sering dimaknai sebagai keadaan yang tidak memberikan ruang kepada orang, dalam waktu tertentu untuk mengemukakan pendapat tentang sesuatu yang telah ada pendapat sebelumnya dalam kerangka pikir yang baku. Inti dari kezumudan adalah orang tidak boleh berbeda pendapat, dan tidak boleh menyimpang dari kerangka pikir awal yang ia gunakan dengan terbukanya ijtihad maka orang boleh berbeda pendapat.
Persoalan selanjutnya untuk saat ini apakah berada dalam masa cemerlang untuk berijtihad atau masih dalam kezumudan? Dan sudah siapkah untuk berubah kerangka pikir ketika menghadapi sesuatu persoalan? Pertanyaan ini cukup mendasar karena akan memberikan dampak pada sifat taat dari seseorang terhadap imamnya[35].
Berbeda dengan itu, dalam aliran tarekat ketaatan murid merupakan sesuatu yang diwajibkan. Dalam bidang ini guru adalah mursyid dan oleh karenanya seorang guru adalah benar dan harus ditaati.
Dari uraian di atas, ketaatan kepada ulil amri akan tergantung pada berbagai hal, bidang, tingkat, ruang, dan waktu. Secara mendasar ketaatan kepada ulil amri dibatasi oleh beberapa hal sebagaimana diuraikan di atas yaitu selama berada pada kewenangan berdasar syariat agama, keadilan, dan kemaslahatan.
- Indonesia
Dalam kasus Indonesia, ulil amri sama seperti ulil amri umumnya dapat terdiri dari berbagai bidang dalam berbagai strata. Tetapi yang lebih menarik adalah membicarakan atau mendiskusikan ketaatan kepada ulil amri bidang pemerintahan karena dapat menjadi bahan diskusi atau perdebatan yang menarik. Hal ini disebabkan, Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, dipimpin oleh seorang presiden berKTP muslim (tanda objektifnya naik haji ke Tanah Suci), tetapi parlemen tidak dikuasai kekuatan politik Islam.
Pertama-tama sebagai dasar yang harus menjadi pijakan dalam mendiskusikan masalah ini adalah berdasar syariat. Dalam hubungan ini apakah ulil amri di bidang politik/kenegaraan/pemerintahan sudah diisi sesuai syariat atau belum. Apabila belum sesuai, maka tidak ada persoalan. Dilihat dari cara pengisian ulil amri bidang pemerintahan (kepala negara) tidak ada pola baku. Tetapi kalau melihat kepada cara pengisian kholifah empat yaitu dipilih, maka pengisian ulil amri (dalam hal ini kepala negara dan kepala pemerintahan) kurang sesuai karena Presiden dipilh oleh rakyat secara langsung tidak melalui MPR seperti dulu.
Sedangkan persyaratan masih menjadi polemic dan perselisihan, misalkan apakah wanita boleh menjadi kepala negara, ini merupakan masalah yang cukup kontroversial sehingga sering membuka diskursus dalam masyarakat. Dalam Al-Qur’an ada ayat yang secara umum menentukan bahwa laki-laki adalah memimpin atas wanita. Apakah ayat ini berlaku juiga dalam pemilihan kepala negara. Ada analog lain, misalnya perempuan tidak boleh menjadi imam laki-laki, kecuali kalau laki-laki itu tidak wenang hukum. Ada lagi satu riwayat bahwa Rosul Saw menyatakan, tunggulah kehancurannya. Ucapan beliau ini keluar ketika beliau mendengar bahwa negeri Parsi dipimpin oleh seorang wanita. Hal ini merupakan masalah syar’i yang sampai sekarang belum tertuntaskan.
Selain itu, walaupun sudah mengalami jaman reformasi, tetapi di Indonesia masih berlaku suatu kondisi bahwa negara adalah segala-galanya, yaitu bahwa negara seolah-olah merupakan asal dan tujuan dari segala gerak kehidupan masyarakat. Dalam menaati ulil amri, selain harus dipenuhi dasar yang diuraikan di atas, secara hukum harus pula dipenuhi beberapa kriteria antara lain, kewenangan/otoritas membuat peraturan, menegakkan keadilan, memajukan kemanusiaan, menciptakan kemaslahatan dan memotivasi yang lurus.
Dengan demikian, secara domestik Indonesia, masih banyak masalah yang layak menjadi kajian objektif tanpa pretensi kecondongan dalam membahas atau membicarakan ulil amri ini.
- Penutup
Berdasar uraian di atas maka kesimpulan pembahasan ini adalah :
- Ulil amri tidak menunjuk pada orang perseorangan tetapi merupakan suatu instirusi atau wadah tempat eseorang atau suatu badan melakukan kewenangannya berdasar legitimasi yang diterimanya. Ulil amri dapat mencakup berbagai bidang baik bidang kenegaraan/publik maupun bidang keilmuan.
- Ketaatan kepada ulil amri akan tergantung pada bidang tempat ulil amri itu berada, dan dibatasi oleh kewenangan, berdasar syariat agama, keadilan dan kemaslahatan.
- Ketaatan kepada ulil amri bidang publik ini ada batasnya, bahkan seseorang yang sedang berkedudukan sebagai ulil amri dan ia telah menyimpang dari syariat Islam, ia harus diganti. Pernyataan harus menandakan bahwa penggantian dapat dilakukan secara baik-baik atau secara paksaan, yang dalam bahasa kesehariaan dikita kenal dengan sebutan kudeta.
- Jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan pemahamaan nash-nash agama, diselesaikan dengan menggunakan kaedah-kaedah perbedaan pendapat yang sudah ada dan biasa dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Pemerintah tidak dapat intervensi dalam persoalan pemahaman terhadap nash, karena hal itu bukan wilayah wewenangnya. Tetapi jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan kemasyarakatan yang bersifat ijtihadi, maka pemerintah dapat memutuskan pendapat mana yang akan diikuti. Misalkan dalam perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal, dalam kitannya dengan pelaksanaan ibadah puasa dan shalat ‘Ied, maka penyelesaiannya diserahkan kepada para pemimpin agama dalam membimbing umat. Tetapi urusan libur ‘Iedul Fithri dan hal-hal lain di luar urusan keagamaan murni, diputuskan oleh Pemerintah.
Sebagai saran, perlu adanya kesiapan kita untuk memulai membuka wacana yang lebih luas tentang pemaknaan ulil amri sehingga tidak terjebak dalam pengertian yang sempit yang menyebabkan kita hidup dalam alam cemerlang tetapi tetap dalam kezumudan.
DAFTAR PUSTAKA
Aceh, Abubakar. 1993. Pengantar Sejarah Sufi dan Taswuf. Solo. Ramadhani.
Ambary, Hasan Muarif, (Dkk). 1996. Ensiklopedia Islam. Suplemen 2. Jakarta. Ictiar Baru Van Hoeve,
Depag, Al-Qur’an dan Terjemahnya
Fakhruddin Hs. 1992. Ensiklopedia Al-Qur’an, Buku 2. Rineka Cipta,
Horrassowitz, Otto. 1993. par 3 History of Muslim, The Philosophers, terjemahan, M.M. Syarif, Para Filosof Muslim. Bandung. Mizan.
Iqbal, Hakim Javid. 1993. Konsep Negara Dalam Islam, dalam Muntaz Ahmad (ed), Masalah-masalah Teori Politik Islam. Bandung. Mizan.
Khallaf, Abdul Wahab. 1984. Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemah Andi Asy’ari dan Afid Mursidi, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jilid Satu. Bandung Risalah.
Mubarok, Jaih. 2000. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung. Rosda.
Pulungan, J Suyuthi. 1997. Fiqh Suyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta. Rajagrafindo.
Roem, Mohamad, Dkk. 1982. Tachta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, Jakarta. Gramedia.
Taimiyah, Ibnu. 1999. As Siyasah Asy-Syar’iyah Fil Islahir Raa’I war Ra’iyyah, Terjemah, Roki Munawar, Siyasah Syari’ah Etika Politik Islam. Surabaya. Risalah Gusti.
Yamani, Ja’far Khodem. 2002 Mukhtasyar Tarikh-I Tharikot-ith-thibb, Terjemahan Tim Dokter IDAVI, Jejak Sejarah Kedokteran Islam, Pustaka Umat.
[1] Anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Periode : 2015-2020, Dosen IAIN Surakarta.
[2] Hasan Muarif Ambary (Dkk), Ensiklopedi Islam, Suplemen 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal.246
[3] Depag, Al-Qur’an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 322, hal. 132
[4] Idem, hal. 245
[5] Idem, hal. 246
[6] Ibid
[7] Fakhruddin Hs, Ensiklopedi Al-Qur’an, Buku 2, Rineka Cipta, 1992, hal. 521
[8] Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemah Andi Asy’ari dan Afid Mursidi, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jilid Satu, Risalah, Bandung, 1984, hal. 64
[9] Abdul Wahab Khallaf, Idem, hal. 64-65
[10] Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, 5: 147
[11] Fakhruddin Loc.Cit
[12] Ibid
[13] Fakhruddin, Op.Cit. 521-522
[14] Fakhruddin, Op. Cit., hal. 246
[15] Idem, hal. 522
[16] Ibnu Taimiyah, As Siyasah Asy-Syar’iyah Fil Islahir Raa’I war Ra’iyyah, Terjemah, Roki Munawar, Siyasah Syari’ah, Etika Politik Islam, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hal.3-10
[17] Hadits yang diriwayatkan Bukhori Muslim, Sesungguhnya kami tidak akan mengangkat seorang yang minta jabatan dalam perkara kami ini; Dalam hadis lain dinyatakan, Barang siapa meminta menjadi hakim dan berusaha untuk itu, maka ia akan terbebani olehnya. Dan barang siapa yang tidak meminta untuk menjadi hakim dan tidak berusaha untuk memintanya (kemudian ia ditunjuk untuk menempati posisi itu), maka Allah akan menentukan malaikat untuk menunjukinya (HR Ahli Sunan). Dikutip dari, Idem, hal. 5
[18] Idem, hal. 10-12
[19] Idem, hal. 13-15
[20] Idem, hal. 15
[21] Idem, hal. 20
[22] Untuk uraian bagian ini lihat, J Suyuthi Pulungan, Fiqh Suyasah, Ajaran, dan Pemikiran, Rajagrafindo, Jakarta, 1997, hal. 102 dst.
[23] Bandingkan, Hakim Javid Iqbal, Konsep Negara Dalam Islam, dalam Muntaz Ahmad (ed), Masalah-masalah Teori Politik Islam, Mizan, 1993, hal. 57-74
[24] Lihat Mohamad Roem, Dkk, Tachta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, Gramedia Jakarta, 1982, hal. 302
[25] Suyuhi, Op. Cit. Hal. 48 dst
[26] Untuk perbandingan secara menyeluruh dalam uraian yang singkat dari keempat Imam Mazhab ii, lihat, Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Rosda, 2000, hal.70-129
[27] Abubakar Aceh, Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawuf, Ramadhani, Solo, 1993, hal. 295-312
[28] Otto Horrassowitz, par 3 History of Muslim, The Philosophers, terjemahan, M.M. Syarif, Para Filosof Muslim, Mizan, Bandung, 1993, ahl. 13
[29] Idem, hal. 36
[30] Idem, hlm. 63
[31] Ja’far Khadem Yamani, Mukhtasyar Tarikh-I Tharikot-ith-thibb, Terjemahan Tim Dokter IDAVI, Jejak Sejarah Kedokteran Islam, Pustaka Umat, 2002, hal. 109
[32] Hadis
[33] Lihat,
[34] Imam mazhab pun terkadang mengalami perubahan pendapat, seperti diperlihatkan oleh Imam Idris. Setelah berguru di Bagdad maka ia berubah dalam memberikan hukum terhadap beberapa hal. Lihat Jaih Mubarok, Loc.Cit.
[35] Coba simak pernyataan ini untuk mencoba sedikit mengukur diri : Pendapat Bapak Pulan berdasar Qur’an dan/atau hadits adalah begitu. Mana yang paling sering digunakan oleh kita dalam berargumen. Argumen demikian, menurut penulis sudah memperlihatkan posisi tempat kita berada pada saat mengajukan argumen tersebut.